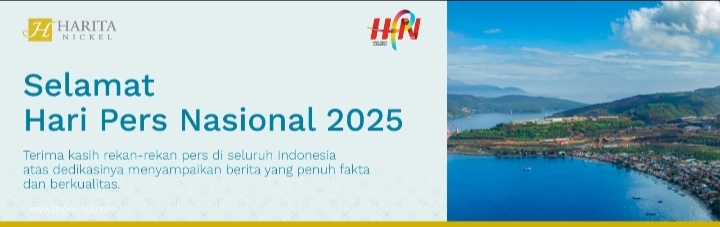INSERTMALUT.com – Kata “integritas” kini mudah ditemukan di mana-mana. Hampir setiap kantor pelayanan publik memajangnya dengan bangga, dari baliho di halaman depan hingga spanduk besar bertuliskan “Zona Integritas” di pintu masuk gedung pemerintahan.
Namun, di balik gaungnya yang begitu sering terdengar, muncul pertanyaan mendasar: apakah makna integritas benar-benar hidup dalam tindakan, atau sekadar berhenti pada tulisan?. Sebab, tidak jarang yang tampak hanyalah simbol—sementara nilai sejatinya belum benar-benar mengakar. Integritas menjadi kata yang diagungkan, tetapi belum sepenuhnya dihayati. Ia dielu-elukan dalam pidato, tapi kadang diabaikan dalam keputusan. Seolah-olah integritas telah menjadi jargon yang kehilangan ruh, lebih sering dipamerkan daripada dijalankan.
Apa itu integritas?
Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan untuk memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Sederhananya, integritas berarti memiliki sikap yang jujur, konsisten dalam ucapan dan perbuatan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai seperti kedisiplinan, tanggung jawab, dan etika.
Ketika Integritas Tak Lagi Sekadar Slogan
Integritas selalu dikampanyekan karena nilainya sangat penting tapi rentan dilanggar. Ia menjadi pengingat agar orang tetap jujur dan konsisten di tengah banyaknya godaan penyimpangan. Selain itu kampanye tentang integritas juga berfungsi mencegah korupsi, membangun kepercayaan publik, menanamkan budaya bersama, serta mewariskan nilai moral lintas generasi. Singkatnya, integritas digaungkan terus-menerus karena ia adalah fondasi kepercayaan dan keberlangsungan sistem sosial maupun organisasi.
Lebij jauh lagi saking pentingnya nilai ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan Survei Penilaian Integritas (SPI) sejak 2016. Program tersebut terus diperbarui metodenya dan diperluas jangkauannya. Tahun ini (2025), SPI kembali digelar secara masif pada Agustus–Oktober untuk memetakan tingkat risiko korupsi di instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah.
Tak hanya itu, baru-baru ini KPK juga menyelenggarakan PERINTIS (Pelatihan Integritas dan Antikorupsi Dasar) dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang diikuti oleh Auditor inspektorat daerah se-Maluku Utara . Upaya ini menunjukkan bahwa integritas bukan sekadar slogan, melainkan fondasi utama birokrasi yang bersih.
Tantangan Integritas dalam Profesi Audit
Dalam profesi audit, integritas bukan sekadar jargon; ia adalah roh profesi. Tanpanya, laporan audit hanyalah formalitas, angka kehilangan makna, dan rekomendasi sekadar dokumen tanpa daya.
Namun realitasnya, auditor sering terjebak dilema. Integritas berbenturan dengan tekanan politik, loyalitas institusi, bahkan ancaman personal. Di titik inilah integritas kerap berubah menjadi sekadar retorika—dipajang dalam visi misi, tetapi sulit diwujudkan dalam praktik.
Birokrasi yang transaksional
Budaya transaksional dalam birokrasi kerap hadir dalam berbagai rupa. Ada yang tampak jelas, seperti kompromi kepentingan ketika auditor ditawari imbalan agar laporan tampak lebih “ramah.” Ada pula yang lebih halus, misalnya konflik kepentingan saat auditor memiliki kedekatan sosial, kekeluargaan, atau hubungan lain dengan pihak yang diaudit, sehingga objektivitasnya tergerus. Bahkan tidak jarang muncul arahan dari pimpinan agar penyajian temuan dilakukan dengan cara yang lebih “proporsional” demi menjaga stabilitas dan menghindari polemik.
Fenomena ini membentuk pola pikir pragmatis—seolah kebenaran bisa dinegosiasikan. Akibatnya, integritas sering tergadai demi keamanan, kenyamanan, atau bahkan promosi jabatan.
Integritas Tak Pernah Usang
Meski digerus pragmatisme, integritas justru semakin penting karena menjadi dasar legitimasi profesi auditor yang hidup dari kepercayaan publik—tanpanya, laporan audit hanya akan dipandang sebagai formalitas birokrasi. Lebih dari itu, integritas adalah jati diri sekaligus ketahanan moral; auditor yang kehilangannya berarti kehilangan otoritas, bahkan pada dirinya sendiri. Di sisi lain, arah reformasi birokrasi mustahil tercapai jika integritas hanya berhenti pada slogan, sebab auditor berintegritaslah yang menjadi katalis perubahan, meski jumlahnya mungkin tak banyak.
Jalan Terjal Menjaga Integritas
Tantangan yang dihadapi auditor internal tidaklah sederhana, mulai dari konflik kepentingan ketika mereka ditempatkan di bawah struktur yang sekaligus menjadi objek audit, budaya permisif yang menjadikan kompromi sebagai kebiasaan sehingga sikap tegas justru dianggap “ganjil,” hingga minimnya perlindungan bagi auditor berintegritas yang sering berujung pada intimidasi, mutasi, bahkan kriminalisasi.Dilema pun muncul: memilih aman dengan kompromi, atau teguh menjaga integritas dengan risiko kehilangan jabatan dan kenyamanan.
Mencari Titik Keseimbangan
Ada beberapa langkah strategis agar integritas tidak berhenti sebagai utopia. Pertama, auditor perlu secara terbuka melaporkan kepada pimpinan apabila terdapat potensi konflik kepentingan, misalnya karena adanya kedekatan kekeluargaan, atau hubungan lain dengan pihak yang diaudit, yang dapat mengganggu sikap profesional dan ketidakberpihakan. Kedua, mendorong digitalisasi proses audit dan transparansi publik untuk mempersempit ruang manipulasi dan transaksi gelap. Selain itu, penting untuk membangun komunitas integritas—lingkungan kerja yang menjadikan kejujuran sebagai budaya bersama, bukan sekadar slogan. Terakhir, negara perlu menyediakan perlindungan hukum bagi whistleblower, agar auditor berintegritas tidak terus-menerus berada dalam posisi rentan ketika memilih bersikap benar.
Belajar Integritas dari Tokoh Bangsa
Mencari teladan, dalam hal apa pun, bukan perkara mudah. Sering kali kita terjebak mencari sosok yang sempurna sebagai panutan, padahal tidak ada manusia yang tanpa cela. Namun, ketidaksempurnaan itu tidak menghalangi kita untuk menemukan sosok-sosok yang mampu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas. Para tokoh bangsa telah memberi teladan nyata tentang bagaimana menjaga integritas, terutama ketika dihadapkan pada pilihan sulit antara kepentingan pribadi dan kepentingan negara.
Dari sekian banyak tokoh bangsa, Jenderal Hoegeng Imam Santoso, Kapolri periode 1968–1971, dikenal luas karena kejujuran dan keteguhannya. Saat menjabat sebagai Kepala Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Sumatera Utara pada 1956, ia menolak ketika rumah dinasnya hendak dilengkapi dengan perabot mewah oleh seorang bandar judi yang bermaksud menyuapnya. Sikapnya yang sederhana namun tegas itu menjadikan Hoegeng simbol integritas sejati—sosok yang tetap lurus di tengah godaan kekuasaan dan rayuan materi, sebuah keteladanan yang kini terasa semakin langka dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia.
Di dunia peradilan, kita mengenal Baharuddin Lopa, sosok yang dikenal tak kenal kompromi terhadap pelanggaran hukum. Ia berani menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, bahkan terhadap sahabatnya sendiri. Ketika mengusut kasus pengadaan fiktif Al-Qur’an senilai Rp2 juta yang melibatkan Kepala Kanwil Agama Sulawesi Selatan, K.H. Badawi, Lopa tetap memproses kasus tersebut meskipun berkali-kali diminta untuk menghentikannya. Baginya, hukum tidak mengenal imunitas—tidak untuk sahabat, keluarga, maupun pejabat negara.
Masih banyak tokoh bangsa lain yang meninggalkan jejak serupa: jejak keberanian, kejujuran, dan tanggung jawab. Dari mereka, kita belajar bahwa menjadi pribadi yang berintegritas dan amanah bukanlah kemustahilan.
Pertanyaannya, maukah kita meneladani langkah-langkah itu, bukan sekadar mengaguminya dari jauh?
Integritas Jalan Sepi yang Menentukan Arah
Pertanyaan apakah integritas masih punya tempat di dunia yang serba transaksional memang sulit dijawab. Namun, satu hal pasti: tanpa integritas, profesi auditor kehilangan legitimasi, dan negara kehilangan instrumen penting untuk menjaga uang rakyat.
Menjadi auditor berintegritas memang jalan sepi—sering tanpa dukungan dan penuh risiko. Tetapi justru karena itulah integritas menjadi semakin berharga. Ia bukan sekadar nilai moral, melainkan warisan yang menentukan arah masa depan birokrasi: apakah kita menuju sistem yang sehat, atau terus terjebak dalam lingkaran transaksional yang tak berujung. (*)
Oleh: Muhammad Amin Iskandar Alam
(Pegawai Negeri Sipil – Auditor)